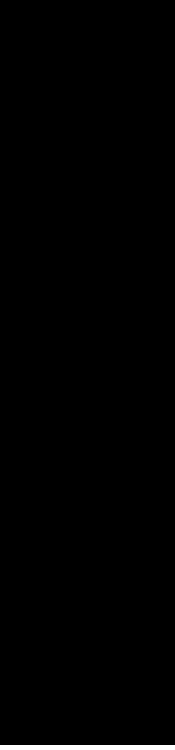MUASAL BATIK SENDANG LAMONGAN

Sifwatir Rif’ah, SE, MM*
Oktober adalah bulan batik nasional bahkan kini secara internasional juga mengacu ke peristiwa ditetapkannya batik Indonesia sebagai Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity oleh UNESCO, lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penetapan ini melewati berbagai penilaian dalam sidang di Abu Dhabi dan inugurasi penetapannya dilakukan di Perancis pada 2 Oktober 2009. Sejak itu batik mendunia, dari anak TK di pelosok Nusantara hingga kepala Negara di berbagai belahan dunia seperti mantan Presiden Amerika Bill Clinton dan Presiden Barack Hussein Obama, Presiden Rusia Vladimir Putin, mantan Presiden Afrika Selatan mendiang Nelson Mandela, orang berpengaruh dunia seperti CEO Microsoft Bill Gates, bahkan legenda sepakbola dunia Zaenuddin Zidan dan David Beckham juga mengenakan batik buatan Indonesia.
Di antara sekian batik yang yang bertumbuh di Nusantara ini ada batik yang berkembang dari desa Sendang Paciran Lamongan yang keberadaannya sudah berjajar dengan batik dari berbagai daerah se-Nusantara sejak mendapat anugerah Upakarti Presiden RI pada tahun 1992 dan memenangkan juara II Lomba Design Batik Nasional pada 2010 serta terlibat dalam berbagai program, event dan ekspo-ekspo di tingkat nasional dan regional.
Tulisan dari hasil riset kecil ini mengupas tentang muasal batik Batik Sendang Lamongan atau selanjutnya disingkat BSL sebagai sumbangsih dan partisipasi desa Sendang dalam meramaikan batik di pentas dunia. Sejak masuk dalam peta industri batik Nusantara melengkapi kekayaan ragam batik dari Yogyakarta, Solo dan Pekalongan yang lebih dulu populer, BSL ini menjadi fenomenal. Berbagai penelitian akademis dari kampus-kampus sekitar Surabaya dan Malang menjadikan BSL sebagai obyek kajian dari berbagai tinjauan. Sejauh ini sudah puluhan judul skripsi, tesis, jurnal dan tulisan lepas tentang BSL meski masih belum banyak dikupas dalam buku yang diterbitkan.
BSL yang dikenal luas hari ini tidak lepas dari perjuangan panjang dan jerih payah para pembatik, saudagar, pengguna, pecinta atau kolektor batik, jajaran pemerintah desa dan pemerintah daerah yang terus menerus menjaga dan memajukan kesinambungan hasil karya adiluhung ini. Jalan panjang nan terjal itu setidaknya tampak hingga tahun 1980-an, BSL yang sudah berkembang sejak tahun 1500-an mengalami stagnasi berkepanjangan setelah kemerdekaan. Baru pada masa khidmat Bupati Lamongan HM. Syafi’i As’ari (1984-1989) dan H. Moch. Farid (1989-1999) juga Gubernur Jawa Timur Soelarso (1988-1993) dan jajarannya, BSL kembali menggeliat.[1] Pada tahun 1984 BSL dianjurkan sebagai seragam pejabat Pemerintah Daerah Lamongan dan sewindu kemudian pada tahun 1992 berhasil masuk ke Istana Negara. Hj Sumikah Ishaq (UD Cahaya Utama/ Jaya Utama) mendapat apresiasi langsung dari Presiden RI Soeharto atas kepeloporan dalam mengembangkan BSL. Anugerah Upakarti Presiden RI tersebut merupakan tonggak penting dalam perkembangan BSL berikutnya di antara batik-batik yang berkembang di Nusantara. Harus diakui, sampai hari ini pembahasan tentang batik Nusantara, terutama dalam publikasi seperti buku terbitan, BSL masih sering terlewati. Oleh karena itu diperlukan upaya sistematis untuk mengangkat BSL dari sisi literasi.
Dalam rentang tahun-tahun setelah peristiwa bersejarah Upakarti, BSL kemudian merambah lebih luas lagi ke tengah masyarakat dan banyak dicari kolektor asing dari Jepang, Australia, Amerika dan Belanda. Fase perkembangan di masa Bupati Masfuk (2000-2010), BSL mulai aktif ekspansi ke luar daerah dengan mengikuti berbagai pameran tingkat nasional di Jakarta, seperti Pameran Produk Unggulan Indonesia (PPI) di arena Pekan Raya Jakarta (PRJ), Inacraft, Crafina dan Gelar Batik Nasional (GBN) di Jakarta Convention Center (JCC) dan lainnya. Pada era Bupati H Fadeli (2010-2020) BSL lebih popular karena masuk ke tengah masyarakat dengan kebijakan wajib mengenakan BSL (tulis, cap dan printing) kepada pegawai dan siswa se-Lamongan, juga secara rutin digelar berbagai lomba design batik untuk memperkuat produk.
Dipelopori Istri Sunan Sendang
Meski belum sepopuler batik dari Solo, Yogyakarta dan Pekalongan, Batik Sendang Lamongan ini dinilai memiliki eksotisme tersendiri dibanding batik tulis pada umumnya. Hal ini karena ekspresi yang terpancar dari guratan BSL memadukan pengaruh klasik Majapahit, nilai Islam dan perkembanga motif kekinian secara harmonis.[2] Secara historis, pembatik di desa Sendang memiliki keterampilan alamiah turun temurun yang terpelihara sejak zaman kerajaan Majapahit, Demak, Giri Kedaton sampai kini, sehingga dari ‘doeloe’ perempuan Sendang dikenal berjemari lentik dan berkulit putih bersih karena jarang terpapar sinar matahari di luar rumah. Dari merekalah batik-batik terbaik dikerjakan kemudian beredar di kalangan bangsawan kerajaan, pejabat-birokrat, kelas menengah ke atas dan seterusnya hingga digunakan masyarakat luas dari semua kalangan pada hari ini.
Setelah Batik Sendang sepopular seperti sekarang, kemudian muncul pertanyaan, bagaimana muasalnya? Keterangan paling banyak menyebut keberadaan Batik Sendang Lamongan dalam khazanah batik nusantara tidak lepas dari keturuan raja Majapahit yang dikenal dengan Raden Nur Rahmat sekitar 500 tahun lalu.[3] Ayahnya adalah Syekh Abdul Qohar bin Malik bin Syeikh Abu Yazid Al-Baghdadi sedangkan ibunya Dewi Sukarsih, putri Tumenggung Sedayu Joyo Sasmitro, keturunan Prabu Brawijaya. Dari jalur ibu inilah Nur Rahmad mendapatkan gelar raden sebagaimana bangsawan pada umumnya zaman itu. Raden Nur Rahmad akhirnya menikah dengan seorang putri dari Kudus, yaitu Raden Ayu Tilaresih, putri Pangerang Ngrenget yang keluarga Kesultanan Demak yang juga berasal dari keturunan Prabu Brawijaya melalui Raden Fattah atau sultan pertama Kerajaan Demak Bintoro. Raden Ayu Tilaresi sejak kecil dikenal dekat dengan bibinya, yaitu Ratu Kalinyamat yang terkenal dengan sebutan Mbok Rondo Mantingan yang masih cucu Raden Fattah.[4]
Pada satu ketika, saat dakwah makin berkembang luas, Sunan Sendang mendapat hadiah sebuah ‘masjid berukir’ dari Ratu Kalinyamat dan Sang Ratu pun berkenan ke Sendang untuk melihat masjid yang sudah terpasang kembali di atas bukit Amintuno hanya dalam satu malam.[5] Dalam kunjungan tersebut Ratu Kalinyamat mengenakan kain batik motif kawung yang elok sampai-sampai mengundang penduduk berdecak terkagum-kagum.
Atas kekaguman tersebut Raden Ayu Tilaresih yang memiliki keterampilan membatik itu kemudian mengajarkan penduduk tentang seni membatik. Keterampilan Raden Ayu Tilaresih ini didapat kerana masa remajanya dihabiskan di sekitar Kudus-Jepara dan sebagimana para putri pada umumnya, ia juga belajar membatik hingga mahir. Berdasarkan kisah yang terpelihara di masyarakat, Raden Ayu Tilaresih kemudian dianggap sebagai pioner dari cikal-bakal tradisi membatik di Sendang. [6] Penduduk sangat antusias belajar membatik sebagai keterampilan tambahan yang dikerjakan sambil menjadi ibu rumah tangga. Sejak itu penduduk Sendang menjadi ‘orang rumahan’ atau pekerja ‘in door’ karena para lelakinya sebagai pengrajin emas di ‘besali’ di samping atau depan rumah, sementara para perempuannya sebagai pembatik di dapur bagian belakang rumah.
Dimotori Veteran Perang Diponegoro
Cerita yang berkembang tersebut di atas bersumber dari ‘folklore’ atau cerita rakyat antar generasi dari masa ke masa yang sudah diuji di kampus-kampus dalam ujian skripsi dan tesis, hingga pada tahun 2016 muncul asumsi baru yang ditulis dalam sebuah buku berjudul “Desa Sendang dan Cerita Rakyatnya”. Buku ini ditulis berdasarkan penelusuran Kiai Baqir Bin Kiai Hasan Syarqowi, seorang tokoh pejuang pendidikan asal Sendang yang kini tinggal di Malang. Sejak muda ia melakukan pencarian fakta tentang Sendang dan seluk-beluknya melalui berbagai jalur, baik emperik-realis maupun rasionalis. Ia menggabungkan sejumlah fakta yang ditemui di lapangan sebagai data primer kemudian menghubungkan dengan data skunder yang pernah ditulis pakar sebelumnya dan istimewanya lagi ‘ditasheh-kan’ secara spiritual dengan ‘lelaku’.[7]
Buku ini tergolong unik karena konteks justifikasi maupun historinya cukup memadai validitasnya meski belum diuji secara ilmiah-akademis. Hal ini karena buku tersebut tidak dideklarasikan semata-mata sebagai kajian historis bernuansa antro-sosiologis, tetapi sepenuhnya dimaksudkan sebagai upaya mendokumentasikan percikan fakta, peristiwa dan kisah-kisah seputar Sendang dari ‘orang dalam’ pada masanya (tinjauan sinkronis) sebab sebelum ini sebagian besar hasil penelitian akademis maupun publikasi popular tentang Sendang dilakukan tidak dari dalam (non-indegenus), adapun tulisan yang saya ini bersifat sebaliknya, yaitu diakranis-indigenus.
Pada zamannya, penulis buku tersebut tergolong sekelompok kecil kalangan yang memiliki data penting terkait Sunan Sendang karena memiliki ‘jalur khusus’ dari pihak keluarga dan pencarian lintas disiplin. Referensi outentik dari yang terdekat dengan Sunan Sendang maupun publikasi ilmiah berbahasa Inggris juga diacu. Dalam penulusurannya, ia mendapati sebuah cungkup di sebelah utara pesarean Sunan Sendang yang dinyatakan sebagai makam Wirokencono dari Yogyakarta dan diyakini sebagai tokoh di balik lahirnya Batik Sendang.[8] Di masyarakat Sendang nama ini tidak popular bahkan nyaris tidak terdengar luas.
Makam Wirokencono tersebut dijadikan acuan di luar yang selama ini menyatakan bahwa muasal Batik Sendang dimulai di masa kehidupan Sunan Sendang pada abad ke-15 M sebagaimana diceritakan secara turun menurun hingga tertuang dalam skripsi, tesis dan jurnal-jurnal ilmiah. Temuan Kiai Baqir Hasan ini adalah ‘novum’ karena menghadirkan versi lain bahwa Batik Sendang baru berkembang antara tahun 1830-an atau setelah perang Jawa yang dipimpin Pangeran Diponegoro. Disebutkan, salah seorang tentara Pangeran Diponegoro bernama Wirokencono melarikan diri ke Sendang kemudian memelopori pembuatan batik. Asumsi ini diperkuat argumentasi bahwa teknik membatik menggunakan canting baru diketahui pada abad ke-17 sehingga dianggap tidak mungkin batik sudah berkembang pada abad ke-15. Pernyataan ini disebutkan merujuk buku ‘The History of Java’ (TS Raffles, 1817) dan Sejarah Malayu Salalatus Salatin karya Tun Muhammad.[9]
Sebagai sebuah temuan, asumsi di atas dapat diterima, namun pendapat yang menyebut teknik membatik dengan canting sudah ada jauh sebelum abad ke-17 lebih kuat berdasarkan penemuan Rouffaer yang membuktikan bahwa canting batik sudah digunakan sejak abad ke-12 M di Kediri.[10] Hal itu diperkuat dengan temuan patung Prajnaparamita pada abad ke-12, mengenakan batik bermotif gringsing yang hanya dapat dikerjakan dengan teknik canting. Juga fakta bahwa motif kawung dan gringsing disebut dalam kitab Pararaton yang ditulis pada tahun 1481 M juga fakta sejarah menunjukkan batik banyak digunakan para bangsawan Majapahit dan di pusat pemerintahan daerahnya,[11] termasuk di Katumenggungan Tuban dan Sedayu yang membawahi desa Sendang.
Terkait tulisan TS Raffles, sejauh penelusuran penulis justru menguatkan temuan Rouffer karena yang disinggung Raffles justru penjelasan tentang perkembangan berikutnya dunia batik di Jawa sebagai pembahas masalah batik paling menarik masyarakat Eropa yang oleh karena itu sejak diterbitkan buku tersebut batik makin terkenal di seluruh dunia.[12] Asumsi muasal Batik Sendang dibawa pelarian veteran perang Jawa dari Yogyakarta pada abad ke-18 mungkin saja terjadi dalam dalam konteks memperkuat masyarakat Sendang yang sebelumnya sudah membatik sebagaimana terpelihara dalam folklore turun menurun berkisah di tengah masyarakat secara ‘mutawatir’ atau tersambung hingga sumber pertama. Dengan demikian, novum ini dapat dinilai sebagai penjelas lebih lanjut bahwa Batik Sendang pada masa itu sudah ada dan Wirokencono yang memiliki keahlian di bidang batik turun memajukan Batik Sendang sehingga berkembang seperti saat ini.
Ditemukan Kembali
Lepas dari hal di atas, perjalanan Batik Sendang Lamongan memang sudah panjang. Sebagai sebuah produk batik adalah hasil cipta manusia yang dapat berubah bahkan lenyap setiap saat. Ada motif Batik Sendang sempat nyaris hilang dari peredaran karena setelah peristiwa Gestapu tahun 1965 hingga tahun 1980-an terjadi puncak stagnasi produksi. Saat kembali memasuki pasar yang lebih luas, motif tersisa tinggal beberapa sehingga yang diproduksi hanya itu dan itu saja. Melihat kenyataan tersebut, HM Ishaq dan Hj Sumikah sebagai pengusaha batik dipercaya Bupati Lamongan H. Moch. Farid (1989-1999) untuk menggali motif Batik Sendang yang pernah ada. Setelah melakukan penelusuran di Sendangagung dan Sendangduwur, diketahui ada seorang pembatik sepuh berumur 75 tahun yang masih dapat mengingat motif-motif yang pernah dibuat saat remaja sebelum tahun 1965. Dari tangan Ibu Marni inilah pada tahun 1995 dibuat duplikasi jenis-jenis motif Batik Sendang dalam dua lembar kain berukuran 1,15 x 2 Meter. Satu buah diberikan kepada Pemerintah Lamongan dan satu lagi masih tersimpan sebagai dokumen milik UD ‘Cahaya Utama’ (BSL Cahaya Utama/ Jaya Utama).
Motif-motif yang berhasil diselamatkan tersebut selanjutnya diperbanyak melalui tukang-tukang batik yang tersebar se-kampung Sendang Komplek, kemudian oleh para pengusaha didistribusikan ke pasar di Surabaya, Jakarta dan tentu di seluruh Lamongan dan sekitarnya. Oleh karena pasar sudah terbentuk maka terjadi ‘repeat’ order sehingga masyarakat pembatik kembali terbiasa dengan motif-motif yang pernah langka tersebut. Setelah bertahun-tahun mengalami metamorphosis namun kekhasan Batik Sendang Lamongan tidak pudar karena memiliki karakteristik tersendiri dibanding jenis batik daerah lain.
Walhasil, Batik Sendang Lamongan berkembang mengiring zaman dengan ciptaan ‘local genius’ yang ‘genuine’ terasa goresannya natural memesona. Untaian guratannya memiliki detail tarikan yang rumit seperti motif ‘byur’ dengan titik-titik hujan yang tidak sama dengan di tempat lain. Motif-motif lainnya bernuansa flora (tetumbuhan, dedaunan, bunga-bungaan dll), fauna (ikan-ikanan, burung, kupu dll) atau nuansa alam raya seperti laut, gunung, gapura dan sejenisnya.
Kini, lahir banyak pengembang batik di Sendang sehingga terpelihara batik motif klasik dan kontemporer. Dinamika Batik Sendang Lamongan ini seperti mengamalkan kredo umum masyarakatnya, yaitu: Memelihara tradisi yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik. Dengan mengakomodasi dua arus tersebut, Batik Sendang Lamongan yang mulai dikembangkan sejak 500 tahun lalu itu, memasyarakat bersama zaman dan menyumbang kebanggaan Indonesia di mata dunia sebagai ‘The Pride and Masterpiece Heritage of Indonesia’.
*Penulis adalah Dosen pada Prodi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Kranji Paciran Lamongan
[1] Lihat selengkapnya: Thoriq, Studi Tentang Motif Batik Sendang Duwur Di Desa Sendang Duwur Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur,Srikpsi di Jurusan Seni dan Design Universitas Muhammadiyah Malang, 2007.
[2] Sisa-sisa pengaruh kuat kerajaan Majapahit berpadu dengan nilai-nilai keislaman terpelihara baik di sekitar pemakaman Sunan Sendang, antara lain tampak dari gapura bentar khas Majapahit dan gapura paduraksa berupa bentangan sayap burung garuda. Menurut Budayawan asal Lamongan Viddy AD Daery, Muhammad Yamin pernah datang ke desa Sendang sebelum kemerdekaan dalam perjalanan ilmiahnya dari Trowulan Mojokerto. Penelitian Yamin tersebut diterbitkan menjadi buku ‘Tata Negara Majapahit Parwa’.
[3] Raden Nur Rahmat atau lebih dikenal dengan Sunan Sendang lahir tahun 1442 Saka atau 940 Hijriyah yang sama dengan tahun 1520 M. Panggilan Raden yang diperoleh dari garis ibunya ini terus disematkan kepada anak turun Sunan Sendang. Hingga tahun 1980-an baik di Sendangduwur maupun Sendangagung banyak dijumpai sesepuh yang disapa dengan panggilan ‘den’ seperti Den Maulani, Den Ah, Den Bik, Den Mus dan lainnya, namun generasi setelah tahun 2000 sudah jarang yang menggunakan sematan tersebut.
[4] Ratu Kalinyamat adalah cucu Sultan Demak pertama Raden Fattah, putri Sultan Trenggono yang diangkat sebagai bupati Jepara. Ia menikah dengan Sunan Prawoto atau Pangeran Hadiri yang tewas di tangan Ario Penangsang. Pada zamannya, Sultan Hadiwijaya Joko Tingki di Pajang mengurusi wilayah Jawa bagian Selatan dan Ratu Kalinyamat menguasai pesisir Jawa. Kekuasaannya sampai ke Jawa Timur termasuk Surabaya sampai Tuban. Melihat posisi Sedayu yang berada di antara pelabuhan Surabaya dan Tuban, maka Sedayu juga adalah termasuk wilayah kekuasaan Ratu Kalinyamat (Tjandrasasmita, 1975:56; Hayati, dkk., 2000:37-38).
[5] Untuk melengkapi dakwahnya, Sunan Sendang bermaksud mendirikan Masjid di atas bukit Amintuno, dan atas saran Sunan Drajat II (Raden Arif, yang seperiode dengan Sunan Sendang), supaya ke Mantingan, Jepara, menemui Nyai Ratu Kalinyamat (Mbok Rondo Mantingan).Selengkapnya lihat, Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan Makam Islam di Jawa Timur, 2003, hlm. 14. Bentuk arsitektural maupun hias ornamental masjid Sendang Duwur dengan masjid Mantingan memang memiliki kesamaan. Tahun pembuatannyapun tidak terlalu jauh, masjid Mantingan diketahui dibangun pada tahun 1481 Ç atau sama dengan 1559 M dari candrasengkala “rupa brahmana warna sari”, sedangkan masjid Sendang Duwur dibangun pada tahun 1483 Ç sama dengan tahun 1561 M dari candrasengkala yang berbunyi “gunaning sarira tirta hayu” (Tjandrasasmita, 1975:56; Hasan, 1994:6-7).
[6] Dalam sejumlah penelitian skripsi dan jurnal budaya tentang Batik Sendang Lamongan, penulis perhatikan hampir semua menulis cikal bakal Batik Sendang bermula dari istri Sunan Sendang, namun tidak menjelaskan dari mana keterampilan membatik itu didapat sebelumnya. Ada ‘missing link’ yang terus menerus diabaikan. Dalam rekonstruksi sejarah, penulis temukan sumber bahwa istri Sunan Sendang adalah seorang bangsawan, putri Pangeran Ngrenget Kudus yang akrab dengan batik sejak remaja. Dari sinilah ditemukan ‘clue’ dimaksud.
[7] Dialog dengan Kiai Baqir di rumah penulis pada tanggal 5 Juli 2017.
[8] Dalam foto-foto komplek makam Sunan Sendang di era 1970-an keberadaan cungkup ini tampak menonjol di bawah makam Sunan Sendang, misalnya terlihat dalam karya Uka Tjandasasmita tentang Arkeologi Islam Nusantara yang menampilkan foto komplek makam Sunan Sendang sebelum tahun 1960-an.
[9] Sulalatu’l-Salatin bergaya penulisan seperti babad dalam Bahasa Melayu dan menggunakan Abjad Jawi. Karya tulis ini memiliki sekurang-kurangnya 29 versi atau manuskrip yang tersebar di antara lain di Inggris (10 di London, 1 di Manchester), Belanda (11 di Leiden, 1 di Amsterdam), Indonesia (5 di Jakarta), dan 1 di Rusia (Leningrad).
[10] Pembahasan tentang asal usul batik diulas di bab sebelumnya, terbukti terdapat banyak referensi yang menyatakan bahwa batik sudah dikenal di Nusantara sejak lebih 1000 tahun lalu.
[11] Lintu, Op.Cit. hlm. 7
[12] Lihat, Baqir, Op.Cit. hlm 17.