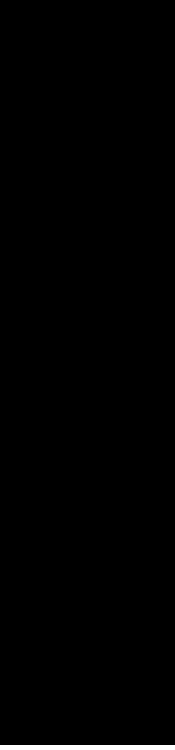NYAMUK NEGERI

Syafi’ul Mubarok
Suara petir menggelegar di angkasa luar, ketika aku tengah berdiri di balik jendela. Awan gelap menyelimuti langit yang sudah terlalu lama tetutup kabut asap. Hujan, sebuah fenomena yang diharapkan oleh setiap kami yang bernapas di balik pekatnya kabut asap yang telah mengungkung setiap diri kami sepanjang hari.
“Moga – moga aja turun hujan”, Fani tiba – tiba saja muncul di balik gorden dapur dengan membawa semangkuk bubur panas. Aku masih saja termenung meratapi kondisi yang tengah menghampiri di sekitar rumah kami. Berkat kabut asap lah kami tidak bisa menambah ilmu, berkat kabut asap perekonomian terus lumpuh.
Fani kemudian duduk sembari melahap bubur yang terlihat masih menyemburkan asap panas, sementara aku masih tertarik dengan kondisi di luar yang batas pandang hanya beberapa meter saja. Menjadi sebuah kewajaran jika tidak ada satu pun kendaraan yang berlalu lalang di tengah jalan yang penuh dengan asap.
Jika pun ada itu adalah bagi mereka yang berani ataupun terpaksa harus keluar rumah. Karena korban akibat penyakit ISPA sudah tidak bisa terhitung banyaknya, mulai dari kecil hingga dewasa, tua hingga muda, semua jatuh akibat menghirup udara tak segar dari kebakaran hutan.
Bola mataku menangkap sorot mobil kendaraan yang tengah beradu dengan kabut asap yang memenuhi udara. Sorot lampu itu semakin dekat dan terus mendekati rumah kami hingga berhenti di pekarangan rumah yang hijau dan kini sudah menjadi kenangan belaka.
“Ada yang datang”, ucapku singkat. Fani pun mulai tertarik dengan perkataanku hingga ia melemparkan buburnya yang hampir habis ke meja kemudian mendorongku untuk melihat seseorang keluar dari mobil yang terparkir di depan rumah.
Seseorang berjas putih menyatu dengan asap tebal dengan mulut berbalut masker berjalan tergopoh – gopoh menuju pintu rumah kami. Beberapa saat kemudian, pintu kami mengeluarkan suara berisik akibat di pukul oleh orang tersebut. Tanpa kusadari Fani sudah menghilang di sampingku.
“Ayah”, teriak Fani histeris ketika membuka pintu rumah kami yang berderit. Aku pun sontak terkaget dan langsung menuju ruang tengah, melihat ayah dengan jas putih yang telah menguning akibat paparan kabut asap.
“Kok nggak bilang – bilang ?”, tiba – tiba Ibu muncul dari dapur. Ayah hanya nyengir terhadap kami semua di tengah keheranan yang melanda. “Ayah hanya mengecek keluarga ayah”, ucapnya singkat.
“Sudah beberapa minggu ini mereka tidak masuk sekolah karena libur akibat kabut asap”, jelas Ibu dengan sedikit agak menggerutu. “Di Padang pun demikian, semua aktivitas belajar mengajar dan perekonomian lumpuh total akibat kabut asap”, katanya tak mau kalah.
“Hujan tak akan turun di langit Indonesia akibat badai El Nino yang menghirup awan musim penghujan yang seharusnya melintasi daratan Indonesia, kini tengah transit di suatu tempat yang ada di muka bumi ini”, ucapnya lirih.
Ayah merupakan seorang dokter yang bekerja di Padang. Jarang sekali ia pulang itu pun jika ada sesuatu yang mendadak dan harus di selesaikan secepatnya. Walaupun demikian, ketika Sumatera dilanda musibah kabut asap ia pun beralih profesi menjadi dokter spesialis pernafasan. Yang tanpa pamrih menolong orang yang membutuhkan, begitu pun kepada keluarganya.
“Sudah lama sekali tanah ini tidak menghirup udara yang segar”, Ayah menatap ke luar jendela. “Kira – kira harus berapa lama lagi kita menunggu kabut asap ini pergi ?”, tanya Fani penasaran. Ia hanya menggelengkan kepala sembari duduk di kursi yang tersedia, begitu pun kami berdua.
Sementara Ibu sibuk kembali dengan urusan dapur, kami pun memanfaatkan momen ini untuk lebih dekat dengan ayah kami sembari bertanya banyak hal kepadanya. “Ayah, apakah tidak ada terobosan dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini ?”, tanya Fani dengan nada agak emosi. Mungkin ia telah rindu dengan oksigen yang telah terlalu lama jauh dari paru – parunya.
“Pemerintah tidak tidur, Fan. Mereka siang malam berusaha menyingkirkan kabut asap dari daerah kita, mulai dari rekayasa cuaca, hingga bom air. Dan bahkan sepanjang jalan yang ayah lalui tadi, ayah melihat beberapa tentara tengah bergelut dengan asap”, jelasnya.
“Kini Indonesia memiliki brand baru untuk bisa menjadi tren di dunia Internasional, Indonesia sebagai pengekspor utama asap ke negeri tetangga”, ucapku sinis sembari bangkit dari kursi dan berjalan mendekati jendela lagi.
Mendengar perkataan itu, Fani hanya tergelak sembari tertawa geli. Sedangkan ayah agak kaget mendengar kata – kata yang terlontar dari mulutku dengan mengelus – ngelus keningnya yang mulai rapuh oleh usia.
***
Suara dentuman musik pesta menggema di setiap sudut ruangan. Beberapa orang dengan memakai jas rapi tengah berdansa untuk merayakan sebuah kemenangan. Ada yang tertawa – tawa, ada juga yang sudah tak sadarkan diri akibat menenggak alkohol tanpa kadar. Di sebuah tempat yang hanya mereka dan tuhan yang mengetahuinya.
Mundur satu bulan yang lalu, di tempat yang sama, dengan suasana yang berbeda. Sekelompok orang berpakaian rapi, ada pula yang berpakaian santai tengah melakukan sidang di depan meja melingkar. Mereka seakan merencanakan sesuatu yang seru.
“Kalau ditebang satu per satu, kita akan rugi hingga 40 % Pak. Jadi alangkah lebih baiknya menggunakan alternatif yang lain”, usul seseorang dengan corak wajah melayu kepada pemimpin rapat. Pemimpin rapat yang seorang sudah berumur pun mengerutkan dahi.
“Di bakar aja”, teriak seseorang berkacamata yang duduk di ujung ruangan. “Jangan, nanti akan menimbulkan bencana kemanusiaan”, nasehat seseorang dengan memakai pakaian sederhana. Mungkin ia adalah penduduk setempat.
Dengan penuh pertimbangan antara ego dan kemanusiaan pimpinan rapat pun memutuskan, “kita bakar habis lahan liar yang ada di utara tempat ini, untuk pembukaan tanah pertanian”. Sontak seluruh ruangan yang hanya berisi 10 orang berteriak setuju dengan keputusan pemimpin rapat.
Namun tidak dengan seseorang berpenampilan sederhana, ia hanya termenung seakan mengetahui dampak tingkah laku mereka merugikan beribu – ribu umat manusia. Beberapa saat kemudian, mereka pun langsung menyalakan api dan menjatuhkannya di lahan gambut yang mudah sekali terbakar di utara tempat itu.
Tak butuh waktu lama bagi si jago merah untuk melahap habis pepohonan maupun tumbuhan baik yang sudah kering atau pun masih muda, begitu pun dengan tanah gambut yang ikut terbakar. 2 Jam kemudian, api telah meluas hingga sampai ke ujung cakrawala. Tanpa sedikit pun memiliki rasa iba, mereka lantas pergi meninggalkan itu semua tanpa ada rasa menyesal yang melekat di dada.
***
Bola mataku telah lelah dengan gumpalan kabut – kabut putih yang bercampur dengan asap sisa pembakaran yang terus mengepul dari tanah gambut yang kini berubah seolah – olah menjadi arang dan batu bara, yang walaupun telah padam tetap memunculkan kabut asap ke udara.
Fani dan Ayah sepertinya telah selesai dengan makan siang mereka. Sementara aku masih terpaku terhadap keadaan yang hingga kini kami belum mengerti sampai kapan musibah ini terus terjadi. Melihat aku memandang ke luar dengan tatapan iba, ayah pun mendekatiku.
“Ini semua adalah ulah nyamuk – nyamuk negeri yang terus menghisap ibu pertiwi tanpa menggunakan hati. Mereka lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan manusiawi”. “Iya Ayah, tapi mereka itu siapa ?”. gerutuku.
Hening sejenak. “Apakah mereka tidak tahu beberapa bulan ke depan kami para pelajar kelas akhir akan menghadapi ujian nasional, dan bagaimana kami bisa menjawab soal – soal yang ada kalau sekolah terus – terusan libur akibat kabut asap”. Belum sempat Ayah berucap aku pun terus mengeluarkan kata – kata keluhanku.
“Apakah mereka tidak tahu kalau Dollar tengah berjaya sementara Rupiah tengah merana, apalagi dengan lumpuhnya kegiatan perekonomian akibat kabut asap, begitu pula dengan label jelek yang dilemparkan oleh bangsa lain kepada ibu pertiwi ?”.
Ayah pun menarik napas dalam – dalam dan menghembuskannya pelan sekali sembari menungguku selesai mencurahkan isi hati yang menyesakkan dada ini. “Sudah selesai ?”, aku hanya terdiam sembari menatap kabut asap yang masih bersantai di luar.
“Nyamuk itu parasit yang harus dibasmi, sedangkan pembasminya adalah pak presiden dan pemerintahannya. Kita tunggu saja nyamuk – nyamuk penghisap kekayaan negeri ini di adili atas perbuatan mereka yang keji”. “Tapi kapan Ayah, kita sudah terlalu capek untuk menunggu”, ucapku.
“Kenapa mereka tidak menyedot asap – asap ini lewat lubang hidung mereka yang panjang sebagai tanggung jawab atas perbuatan yang telah mereka lakukan, dasar nyamuk negeri”, ucapku sinis.
Melihat hal tersebut Ayah hanya mengelus kepalaku sembari berbisik, “suatu saat kamu akan mengerti buah dari kesabaran yang telah kamu tanam benihnya”. Tatapanku kosong menerjang kabut asap yang ada di luar, sebuah tatapan penuh pasrah dari salah seorang pelajar Indonesia yang tengah rindu akan udara segar.
Sampai – sampai otak terasa sakit bukan karena memikirkan ujian – ujian yang siap mendera, melainkan ikut memikirkan bagaimana kabut asap ini bisa musnah dari muka bumi. Saking pekatnya kabut yang menyelimuti, serasa hidup di atas awan layaknya di pegunungan.
Entahlah, aku hanya bisa menyongsong sepi ke penjuru negeri. Mencari jawaban yang sekiranya berarti. Membuat surat dan dikirim ke bapak presiden pemimpin negeri. Sampai kapan pun aku dan beribu – ribu temanku akan tetap mengingat situasi ini, kondisi tanpa udara bersih.
Bersyukurlah kamu yang masih bisa menghirup udara bersih dengan gratis. Karena kamu akan menyesal telah menyia – nyiakan kondisi yang serba gratis itu ketika diselimuti oleh udara kotor nan tercemar yang berbalutkan kabut asap